
Tim Penulis: Jaka Hendra Baittri, Febrianti, dan Rus Akbar Saleleubaja.
Fotografer: Uyung Hamdani
Desain: Ray
Ujung parang Robert Choi Sakombotu menancap ke buah kelapa yang sudah jatuh dari pohonnya. Pemuda berusia 36 tahun itu kemudian mengayunkan parangnya ke belakang untuk memasukkan buah itu ke orek, keranjang rotan khas Mentawai yang tersandang di punggungnya.
Ia bergegas mengumpulkan semua buah kelapa yang telah jatuh sendiri di kebunnya sebelum hujan turun. Dia cemas melihat langit yang semakin gelap karena mendung.
Setelah orek di punggungnya penuh, ia membawanya ke pondok di ladangnya itu. Ada tempat kelapa yang dipagari kayu di pondoknya untuk menampung ratusan buah kelapa. Jika sebelum hujan tidak ia kumpulkan, buah-buah yang bernama latin Cocos nucifera itu akan hanyut ke mana-mana.
“Hujan sehari saja dari pagi sampai malam, besok pagi kita harus berenang, banjir bisa sepinggang. Jadi, sebelum hujan saya harus mengumpulkan semua kelapa ke pondok agar tidak hanyut terbawa arus, begitu mencekamnya sekarang,” kata Robert Choi di pondok ladangnya pada pertengahan September 2025.
Ladangnya di empat lokasi dengan luas total 10 hektare itu, berada di dataran yang tak jauh dari pantai Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ladang itu ditumbuhi tanaman campuran, seperti kelapa, pisang, pinang, durian, langsat, petai, manggis, jengkol, dan nangka.
Sedangkan ladang lainnya seluas 6 hektare berada di perbukitan. Di sana ditanami cengkeh dan pala.

Lahan Robert Choi tidak hanya di desa kelahirannya itu, tetapi juga di Desa Goisooinan di sebelahnya. Lahan seluas 20 hektar itu berupa hutan alam yang ditumbuhi kayu-kayu besar, tempat andalannya untuk material ketika membangun rumah kayu dan membuat sampan tradisional.
Ia juga mempunyai lahan di Pulau Siburu yang terletak di depan Tuapeijat, pusat Kabupaten Mentawai. Di sana ada empat hektar kebun ditumbuhi kelapa, cengkeh, dan pala.
Dari ladang kelapanya di Matobe yang memiliki sekitar 500 batang pohon kelapa, dalam sehari Robert Choi bisa memanen 300 butir buah kelapa yang jatuh sendiri.
Buah kelapa itu ia olah menjadi kopra. Dari kopra yang dijualnya ke pedagang pengepul, sebulan ia menghasilkan Rp5 juta hingga Rp6 juta. Sedangkan buah-buahan lain, seperti pinang, pala, dan cengkeh juga menghasilkan uang.
“Hasil dari kebun ini bagi saya lebih dari cukup. Tanah Pulau Sipora ini sangat kaya dan subur, tidak perlu memakai pupuk dan spesifikasi,” ujarnya.
Meski menyandang gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Robert Choi memilih menjadi petani menggarap lahannya sendiri.
Menurutnya hutan masih menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di Sipora. Selain menjadi bahan untuk membangun rumah dan membuat sampan, juga mengambil manau.
“Hutan juga berisi pohon buah-buahan seperti durian dan langsat yang bisa dipanen sepanjang tahun,” katanya.
Di Sipora, jelas Robert Choi, pembukaan ladang masih dilakukan secara tradisional, seperti yang dilakukan nenek moyangnya dulu. Pembukaan ladang baru dimulai dengan penentuan lokasi dengan mencari tanah pinggiran kota yang dekat dengan sumber udara dan lokasinya tidak terlalu curam.
Setelah menemukan lokasi, dilakukan pembersihan belukar. Onggokan belukar dari pembersihan lahan tidak dibakar, melainkan dibiarkan di tanah sampai lapuk sendiri.
“Membakar lahan tidak dilakukan agar tanaman yang masih berguna seperti tanaman obat tidak ikut mati,” ujarnya.
Setelah itu, tanaman muda untuk kebutuhan pangan segera ditanam, seperti pisang, ubi, talas, keladi, palawija, sayuran, cabe, dan jahe-jahean. Setelah akarnya tumbuh, barulah pohon besar mulai ditebang.


Tetapi pohon yang ditebang hanya yang diperlukan untuk membuat rumah dan sampan, seperti pohon kruing, meranti, dan katuka, tetap dibiarkan tumbuh.
“Saya juga masih mengikuti kearifan lokal ini, misalnya setiap bulan saya masih terus menanam kelapa. Proses menanamnya dilakukan menjelang purnama, itu waktu yang pas untuk menanam kelapa, saya selalu ikuti ini agar hasil kelapanya bagus,” katanya.
Masalah yang dihadapi Robert Choi saat ini adalah banjir yang semakin sering terjadi. Menurutnya, hal itu terjadi akibat aktivitas di hulu sungai.
“Banjir sangat terasa dalam tiga tahun terakhir, itu karena penebangan hutan marak di hulu sungai, ada yang untuk ladang dan ada yang hutannya ditebang perusahaan kayu,” ujarnya.
Robert Choi mengaku pohon-pohon di lahan hutan kaumnya juga pernah ditawar untuk ditebang.
“Saya pernah menolak sekitar dua tahun lalu, mereka menawari uang Rp1 miliar, juga menawari saya sepeda motor, tetapi tetap saya tolak karena hutan itu sangat penting bagi kami,” katanya.
Rencana masuknya PT Sumber Permata Sipora (PT SPS) yang telah mengantongi persetujuan komitmen PBPH atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan seluas 20.710 ha di Pulau Sipora juga meresahkan Robert Choi. Luas izin tersebut hampir sepertiga Pulau Sipora.

“Itu akan semakin memperparah kerusakan lingkungan di Sipora. Hari ini saja setengah hari hujan, banjir bisa sampai satu meter, apalagi ada penebangan berskala besar,” ujarnya.
Ia memperkirakan, jika perusahaan itu beroperasi maka hujan satu jam saja kemungkinan bisa menimbulkan banjir besar yang disertai lumpur. Situasi seperti itu pasti akan merusak tanaman.
“Banjir pasti akan semakin parah melanda ladang saya. Saya rutin memancing di tengah laut di depan Matobe dan sering melihat Pulau Sipora dari kejauhan. Kalau hutannya gundul, benar-benar kiamat sudah,” katanya.
Hampir sama dengan cerita Robert Coi, mantan Kepala Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan, Marius mengatakan warga di kampungnya dalam kondisi santai, dalam seminggu bisa mendapatkan Rp1,5 juta dari hasil ladang.
“Itu sesantai-santainya mengurus kopra, belum lagi yang lain,” ujarnya.
Karena itu, terkait tawaran uang untuk penebangan hutan oleh perusahaan kayu, yang hanya ratusan ribu rupiah, menurut Marius itu sangat merugikan.
Baca Juga: Mencari Air yang Kian Sulit di Sikabaluan


Jika laki-laki di Sipora mengelola ladang, maka kaum perempuan mendapatkan sumber ekonomi dari rawa dan sungai. Mereka mengelola kebun keladi di rawa dan membudidayakan toek di sungai.
Toek bahkan sudah menjadi sumber pendapatan penting untuk kaum perempuan di Sipora, terutama di Desa Matobek, Desa Saureinuk, dan Desa Goisooinan.
Toek adalah jenis moluska. Bentuknya mirip cacing. Nama latinnya Bactronophorus sp, moluska dari kelas bivalvia yang secara alami hidup di dalam kayu mati di sungai yang berair payau.
Toek bukanlah makanan yang tersedia secara alami, seperti lokan atau siput bakau. Harus ada upaya proses budi daya di dalam potongan-potongan batang pohon bak-bak (Campnosperma auriculate) atau pohon tumung (Arthrophyloum diversifollium) yang direndam di dalam sungai berair payau.
Di Desa Matobe, Saureinu dan Goisooinan, toek tak lagi sekadar hidangan rumah tangga. Hari ini toek menjadi sumber penghasilan para perempuan untuk menopang ekonomi keluarga.

Keterampilan membudidayakan toek yang didapatkan turun-temurun juga berkembang menjadi penopang ekonomi lokal. Denyut usaha ini paling terasa di sepanjang Sungai Saureinu, sekitar 5 kilometer di utara Desa Matobe. Kayu-kayu toek berjejer rapat memenuhi tepi kiri dan kanan aliran sungai.
Rita Maspita, perempuan 37 tahun yang lahir dan besar di Desa Saureinu, menyebutkan bahwa toek adalah tabungan yang terbenam di dalam air bagi kaum perempuan di kampungnya.
Ibunya adalah orang pertama yang mengenalkan cara membudidayakan toek kepadanya dan membuat Rita paham seluk-beluk budi daya toek.
“Hanya anak perempuan yang diajarkan, karena membuat toek dianggap pekerjaan perempuan,” ujarnya.
Saat masih kecil, ibu dan neneknya kerap mengajak Rita ke pinggir sungai untuk melihat aktivitas budi daya. Ini terus dijalaninya hingga ketika remaja kemudian ia diajarkan membuat batang toek dan menaruhnya di dalam sungai.
“Mulai dari mencari pohon bak-bak, memotongnya, mengikatnya, dan merendamnya di sungai,” katanya.
Proses pembuatan kayu toek, kata Rita, dimulai dari menggulingkan kayu-kayu yang sudah dipotong ke sungai, lalu merangkainya dengan paku dan tali, dan menambatkannya di sungai.

Proses penebangan dan memotong kayu dengan ‘sinso’ (chainsaw atau gergaji mesin) biasanya mereka upahkan kepada laki-laki.
Untuk membuat sarang toek, pohon jenis bak-bak atau tumung ditebang di ladang dan dipotong-dipotong sepanjang 50 hingga 70 cm. Setelah dibiarkan dua minggu agar getahnya mongering, baru digulingkan ke tepi sungai.
Setelah diberi pengikat dengan tali dan paku lalu direndam di dalam sungai dengan mengikatnya ke pohon nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Dalam rentang tiga hingga delapan bulan toek sudah bersarang di dalamnya.
“Syaratnya hanya satu, sungai harus masih menerima air pasang dari laut. Jika hanya sungai air tawar, toek tidak akan jadi atau tidak muncul,” kata Rita.
Karena itu, warga desa di bagian hulu sungai tidak tidak bisa membudidayakan toek, karena air sungainya hanya air tawar. Itu pula sebabnya budi daya ini hanya bisa dilakukan di desa-desa
“Sekarang toek sudah dijual dan penggemarnya sangat banyak. Tapi tidak semua perempuan terlibat membuat toek, karena pekerjaannya cukup berat,” katanya.
Sejak masyarakat Mentawai marak menggunakan media sosial seperti Facebook, para pembudidaya semakin gampang menjual toek. Cukup memposting foto, harga, dan lokasi, maka calon pembeli akan datang.
“Toek dihasilkan perempuan dan uangnya juga untuk perempuan, jadi tidak perlu minta ke suami kalau ingin membeli sesuatu,” kata Rita tersenyum.
Sekali panen toek Rita biasanya mendapatkan 15 bungkus. Dengan harga per bungkus Rp20 ribu, ia mendapatkan Rp300 ribu.

Rita membudidayakan toek di bawah jembatan Sungai Saureinu. Ia mengaku sumber pendapatan utamanya saat ini berasal dari budi daya toek. Namun jika belum bisa dipanen, dia akan mencari lokan.
“Kalau kayu toek saya belum berisi, saya mengambil lokan dengan menyelam di sungai, dan itu rata-rata sehari bisa menghasilkan Rp200 ribu. Uangnya bisa untuk belanja sehari-hari dan tabungan,” ujarnya.
Menurut Rita, saat ini ancaman utama budi daya toek adalah banjir. “Apalagi kalau airnya keruh, semua bisa mati di dalam kayu,” katanya.
Penyebab banjir datang dari hulu Sungai Saureinu yang hutannya telah ditebang dua tahun lalu. Karena itu setiap kali hujan, sungai itu mengantarkan air yang berlumpur.
“Kalau banjir toek dan lokan jadi mati, padahal itu sumber pendapatan utama kami,” ujarnya.
Rita mendengar akan masuknya perusahaan kayu PT SPS (Sumber Permata Sipora) yang akan menebang hutan yang lebih luas di Pulau Sipora.
“Kami tentu sangat menolak rencana ini, semoga itu tidak jadi dilakukan, bisa habis toek dan lokan di sungai ini,” katanya pertengahan September 2025.

Penebangan hutan skala besar di hulu sungai Saureinu dan Sungai Goiso Oinan terjadi sejak awal 2022. Kondisi ini membuat Kepala Desa Saureinu Tirjelius Taikatubutoinan resah.
“Karena banjir mulai sering datang. Banjirnya pun lain dari biasa, airnya keruh bercampur lumpur, hujan saja satu hari seperti sekarang langsung banjir,” katanya.
Menurut Tirje, masyarakatnya sangat tergantung dengan air sungai, karena selain untuk budi daya toek, juga anak-anak sungainya menjadi sumber air minum.
Sebab akibat penebangan, selain kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan perpecahan antarsuku, setelah perusahaan kayu pergi. Belum lagi rencana penebangan skala besar dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT SPS.
“Seharusnya semua pihak belajar dari masa lalu,” ujarnya.
Tirje menceritakan pada 1990-an, ketika perusahaan kayu masuk menebang hutan dan masyarakat menerima fee kayu, mereka menghamburkan uang yang diterima dalam sekejap.
“Mereka hidup elit [mewah] saat ada uang dan saat perusahaan itu pergi, mereka kembali miskin dan hutannya habis, konflik sosial pun terjadi,” kata Tirje.
Konflik antar keluarga dan antarsuku juga meningkat, karena ada yang menyerahkan lahan komunal yang tidak disetujui anggota keluarga lain.
“Pola ini kembali terjadi sekarang, harusnya masyarakat sadar dan tidak melakukan kesalahan itu kembali,” ujarnya.
Ia memastikan lahan hutan adat tidak akan bisa masuk ke dalam wilayah konsesi penebangan.
Kami mendatangi Desa Bosua dan melihat bagaimana turis asing wara-wiri membawa papan selancar. Pembangunan beberapa resort dan surf camp masih berlangsung di beberapa titik.
Ombak di Katiet terkenal dengan nama “Lance’s Right”. Ini diambil dari nama Lance knight, seorang peselancar internasional yang tergila-gila dengan ombak negeri para sikerei ini dan pertama menjajalnya.
Ombaknya berwarna tosca dan punya gradasi sangat halus ke warna cokelat muda saat terhempas ke pinggiran pantai. Peselancar-peselancar ini datang dari bermacam negara. Maxim Gouchen, salah seorang warga Perancis yang sudah 13 tahun tinggal di sana mengatakan ada beberapa peselancar dari Quicksilver yang sedang menikmati ombaknya.



Maxim pemilik Lances Right Surf House. Dia sudah 13 tahun berada di Indonesia. Dia yakin berinvestasi melalui penanaman modal asing (PMA) dalam bentuk surf house atau resort di Desa Bosua menjanjikan.
Tapi kini berita-berita perizinan perusahaan kayu di perbukitan Bosua yang sungai besarnya langsung menuju area surfing membuatnya cemas. Itu adalah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT SPS.
Dia mengaku tak bisa berpendapat banyak, namun tentu saja rasa cemas ada karena berita tersebut. Dia berharap banyak pihak memiliki kesadaran akan pentingnya hutan terhadap ekosistem di kawasan mereka.
“Saya tentu saja cemas mendengar cerita itu, tidak hanya pohon yang hilang, tapi juga ada monyet di dalamnya, ada burung rangkong. Saya hanya sedih kalau itu terjadi, tapi saya tidak bisa bilang sesuatu, karena saya warga negara lain,” ujarnya.
Kecemasannya bukannya tak beralasan. “Peselancar datang dari Amerika, Jerman, Spanyol dan negara-negara lain, mereka sangat senang melihat Mentawai yag sangat alami dan masih banyak hutan yang cantik,” katanya.
Irman Jhon, kepala Desa Bosua mengatakan jika ada penebangan yang kemudian berdampak kepada laut di Bosua akan dapat menyurutkan minat peselancar dari banyak negara. Kondisi itu akan diikuti pergeseran sumber ekonomi desanya.
Menurutnya ada miliar uang yang berputar di Bosua, termasuk dari Katiet yang merupakan favorit para surfer.
“Termasuk penjualan tanah, pertanian, dan usaha yang dibuka warga. Ada yang berdagang, ada yang beli material bangunan yang juga dari warga, kalau bicara putaran uang itu miliaran rupiah,” katanya.
Dia yakin ancaman terhadap kelestarian lingkungan juga akan mengancam minat para turis asing. Karena itu, Irman berharap pemerintah harus memperjelas tentang rencana izin tersebut.
“Kadang kalau suara dari desa ini tidak ada apa-apanya. Kalau tingkat kabupaten sudah boleh, ya sudah, sebesar apa pun suara kita nggak akan didengar. Tapi yang dirugikan nantinya ya kabupaten lagi,” kata Irman.
Nama Irman John diketahui sebagai salah satu kepala desa yang menandatangani surat persetujuan masuknya PT SPS ke Sipora. Namun, Irman mengatakan surat yang pernah dia tanda tangani hanya satu kali yang diberikan oleh orang dari perusahaan yang melakukan sosialisasi ke Desa Bosua.
“Sebelum saya tanda tangani saya baca dulu, dan surat itu menerangkan bahwa pihak PT SPS sudah melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat dan kepala adat di Bosua, lalu saya tandatangani. Itu bukan surat dukungan terhadap perusahaan, tapi kalau kemudian surat itu sudah berubah saya tidak tahu,” kata Irman John.
Saat pembahasan Amdal PT SPS di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat di Padang pada Mei 2025, Irman juga tidak hadir karena tidak ingin dianggap sebagai bentuk dukungan kepada perusahaan.
Dia keberatan dengan dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi.
“Jangan gara-gara itu minat para pesurfing itu jadi surut, lautnya kotor, banyak sampah dan lainnya. Di sisi lain yang dirugikan negara, terlebih kabupaten, satu orang yang surfing dipungut retribusi Rp2 juta sekian, miliaran yang dipungut kabupaten,” katanya.
Keberatan terhadap rencana masuknya PT SPS dikatakan Sandri Antoni, kepala Dusun Moria, Desa Betumonga, Sipora Selatan.
Dalam lima bulan terakhir, pria 45 tahun itu menyaksikan truk pengangkut kayu hilir-mudik dari hutan ke sebuah logpond di pantai Taraet, tempat ia mengumpulkan gurita. Hutan di sana sedang ditebang melalui izin SIPUHH yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Ia juga menyaksikan beberapa kali kapal ponton datang dan pergi dari logpond membawa ribuan kubik kayu ke luar Mentawai. Rencana masuknya PT SPS yang memiliki wilayah penebangan yang lebih luas dan lama, membuatnya khawatir.
“Menurut saya tidak boleh lagi menggunduli hutan, harus tetap kita jaga. Karena, satu, hutan itu tempat binatang. Binatang bisa punah kalau hutannya ditebang terus. Kedua, bisa menimbulkan banjir, longsor, itu dampaknya,” katanya.
Selain itu, tambahnya, hutan diperlukan untuk bahan bangunan. “Tentu kita butuh kayu, papan. Kalau sudah habis kayu diambil perusahaan, kalau mau bikin papan di mana lagi kita ambi kayu,” kata Sandri.
Kehidupan warga saat ini, lanjut Sandri, sangat tergantung dari hutan, ladang, dan laut.
“Kalau kehidupan di darat tergusur karena masuknya perusahaan kayu, terpaksa kita bergeser ke laut, dan di laut risiko lebih besar, bisa tenggelam,“ ujar pengepul gurita itu.
Sebenarnya, kata Sandri, banyak masyarakat biasa seperti dirinya tidak setuju dengan banyaknya penebangan hutan di Pulau Sipora. Namun, mereka tidak berdaya karena bukan pemilik lahan.
“Yang setuju dengan perusahaan kayu ini kan tuan takurnya, tuan tanah, karena mereka yang dulu menemukan kampung ini, tentu mereka yang berhak. Kita yang pendatang hanya menumpang saja, kami tidak bisa larang,” kata Sandri.
Karena PBHP PT SPS dan izin penebangan hutan lainnya dari pemerintah, ia berharap pemerintah menghentikannya.
“Kalau pemerintah mau putuskan hubungan itu, mudah-mudahan masyarakat di sini bisa menjaga alamnya,” katanya
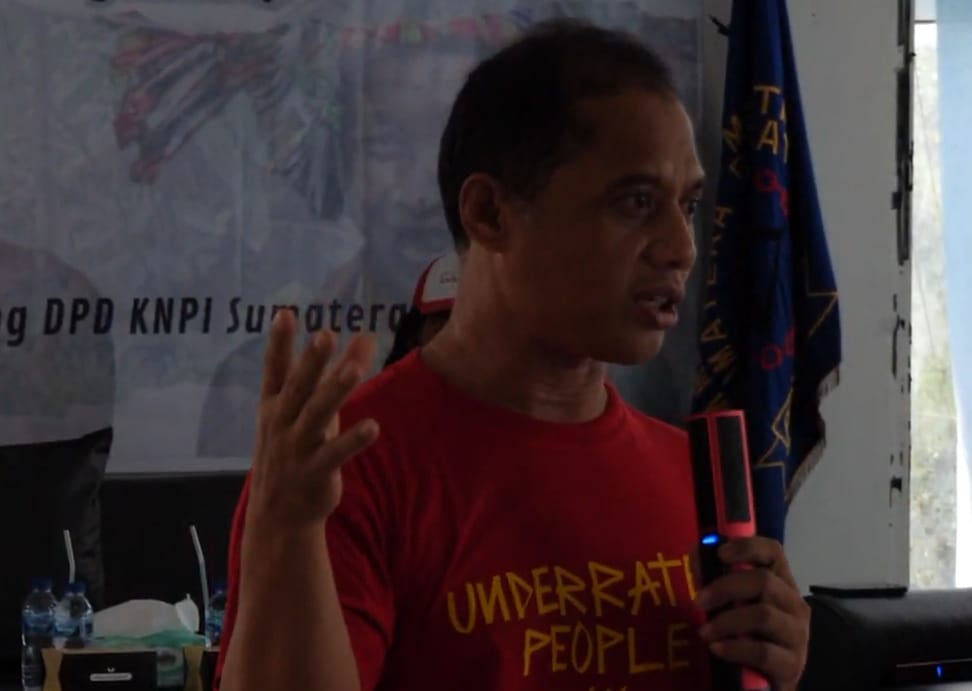
.Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia Amalya Oktaviani mengatakan masyarakat adat di Pulau Sipora sudah membentuk sistem ekonomi sirkular yang bergantung pada keberadaan hutan.
Menurutnya, nexus antara hutan, ketahanan pangan, dan sumber penghidupan masyarakat adat adalah hal penting yang harus dijaga keseimbangannya.
“Berdasarkan itu, masuknya PBPH PT SPS harus dikritisi lebih lanjut, terutama terkait prosedur masuknya izin tersebut. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia mendorong kebijakan pulau kecil tanpa industri ekstraktif, demi menjaga keberlanjutan ekosistem di Pulau Sipora,” ujarnya.
Terkait rencana masuknya PT Sumber Permata Sipora yang telah mengantongi persetujuan komitmen PBPH seluas 20.710 ha di Pulau Sipora, menurut Rifai Lubis persoalan utamanya adalah masalah perlindungan ekosistem dan perlindungan Sipora sebagai pulau kecil.
Direktur Yayasan Cita Mandiri Mentawai itu mencontohkan ketika Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Garuda pada awal Oktober 2025 menyita hasil kayu yang diduga dari tebangan ilegal PT BRN di hutan produksi di Sipora dengan takiran kerugian Rp240 miliar.
“Bila kita baca estimasi kerugian sekitar Rp240 miliar yang ditaksir Satgas PKH, dari jumlah itu nilai kayu yang hilang hanya sekitar Rp47 miliar, sisanya hampir Rp200 miliar adalah kerugian ekosistem,” ujarnya.
Itu artinya, lanjut Rifai, dengan penebangan pada sekitar 700 hektare saja, kerugian ekosistem sudah mencapai Rp200 miliar.
“Bayangkan jika sampai 20.000 hektare ditebang, kerugian ekosistem bagi Sipora akan berkali-kali lipat dan itu akan ditanggung negara apabila PBPH itu sampai beroperasi,” katanya.
Jika tujuan pembangunan adalah perlindungan lingkungan, kata Rifai, maka baik aktivitas ilegal maupun yang berstatus legal yang merusak ekosistem seharusnya tidak menjadi pilihan. (*)
Liputan ini didukung oleh Trend Asia
Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!
©2025. Roehana Project